 |
| (Nuriman, S.H - Kepala Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Hukum LBH Polem) |
Dulu, aku adalah penganut keyakinan keras: kelas sosial itu bisa dimatikan. Caranya tidak rumit, cuma satu: ganti sistem ekonominya.
Wajar jika aku berpikiran begitu. Lahir dari keluarga sederhana—bapak buruh pabrik yang berpeluh dan ibu yang bekerja serabutan untuk menopang ekonomi—secara emosional, aku punya hubungan yang sangat intim dengan semangat Sosialisme-Komunis. Aku muak melihat kepemilikan modal dikuasai segelintir orang dan fenomena kelas yang menyertainya. Semangat perlawanan ku menggelora; aku benci melihat mereka yang bersikap sombong hanya karena harta dan jabatan.
Namun, setelah kenyang mengikuti berbagai diskusi lintas ideologi di kampus, aku menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih menjengkelkan daripada ketimpangan itu sendiri: kelas sosial tidak pernah mati. Ia tidak hilang. Kelas itu hanya pindah. Bukan pindah ke struktur ekonomi yang baru, melainkan pindah ke tempat yang paling sulit dijangkau oleh revolusi: ke dalam kepala dan jiwa manusia.
Sosialisme-komunis secara teoritis ada benarnya mengatakan bahwa pangkal dari terbentuknya kelas sosial karena kepemilikan modal yang dikuasai oleh individu dalam suatu proses produksi. Modal perusahaan yang dimiliki oleh segelintir individu atau satu individu akan berdampak pada pembagian nilai tambah (keuntungan) yang timpang. Pemilik modal sudah pasti akan mengambil keuntungan besar untuk pihaknya. Sementara buruh yang telah bekerja dengan keras dan melelahkan hanya mendapat bagian yang sedikit. Pada proses produksi dibawah sistem seperti itu maka pemilik modal akan semakin mendapat kekayaan sedangkan buruhnya justru hanya mengalami stagnasi ekonomi. Meskipun demikian ketimpangan bisa lahir juga dari negara dan rezim sosialis.
Aku menyaksikan fenomena sosial yang lahir dari ekosistem kapitalis-liberal. Ia membentuk individu yang sombong dan menghina manusia yang lemah. Pengalaman dalam melihat fenomena itu aku saksikan di suatu industri jasa kesehatan rumah sakit. Ada semacam aturan tak tertulis pada praktik pelayanannya. Perbedaan perilaku yang tajam kerap terlihat dari substansi perintah oknum atasan untuk customer beruang banyak dan sedikit. Perbedaan itu menghasilkan skala prioritas pelayanan yang mengalami pergeseran. Alih-alih berdasar tingkat risiko kesehatan, justru seakan sibuk mengintip tebal atau tipisnya dompet customer (pasien). Suasana menjengkelkan terjadi jika customer berjiwa kapitalis itu sudah mulai menunjukkan kesombongan dan menghina customer lain yang lemah secara materi karena ia merasa dirinya adalah pasien prioritas (karena hartanya). Kekayaan materi memang cenderung mudah mempengaruhi individu untuk bersikap sombong.
Sebuah ironi, ketika rumah sakit itu melabeli dirinya sebagai lembaga berprinsip syariah namun realitanya masih ada sikap, perilaku dan perintah yang bernuansa materialistik. Fenomena itu jelas kontradiktif dengan kaidah Maqasid Syariah yang menjadi tujuan perlindungan dalam hukum islam, salah satunya hifdz al-nafs (melindungi jiwa). Hifdz al-Nafs berarti bahwa skala prioritas pelayanan itu seharusnya bersandar pada risiko kesehatan jiwa bukan pada uang yang ada di dompet atau rekening customer. Jika materi menjadi dasar prioritas, maka kekhawatirannya ialah tumbuhnya sikap angkuh dan sombong. Ibarat kisah Azazil yang menolak sujud kepada Adam atas perintah Allah Swt karena ia merasa tinggi secara materi sebab dicipta dari api bukan dari tanah. Atau seumpama kisah Qarun yang sombong karena hartanya yang melimpah.
Aku ingin menjelaskan, tulisan ini berangkat dari tesis bahwa masyarakat tanpa kelas tidak mungkin terwujud hanya melalui rekayasa struktur ekonomi, tanpa transformasi moral individu.
Perenungan Filosofis Tentang Arti Tanpa kelas
Tujuan besar sosialis-komunis untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas terus menjadi perdebatan teoritis yang tak berkesudahan. Namun lambat laun aku berpikir lebih dalam tentang usaha meniadakan kelas sosial itu apakah berhenti pada persoalan materi belaka atau justru beriringan dengan dimensi imateril yaitu moralitas.
Masyarakat tanpa kelas yang hidup dalam prinsip kolektif dengan upaya dominasi kepemilikan modal oleh negara, versi sosialis-komunis, maupun masyarakat kelas yang hidup dalam prinsip kebebasan individu dengan minimalisasi kepemilikan modal negara, versi kapitalis-liberal, tidak berarti apapun jika setiap individunya bersifat adigang-adigung-adiguna (peribahasa jawa yang memiliki arti sombong atas kekuatan, kekuasaan, kekayaan dan kepandaian).
Perkara sombong karena kepandaian pernah diingatkan oleh Bapak Republik, Tan Malaka (Pemikir komunis Indonesia), mengatakan bahwa bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Dari nasihat itu, aku menyadari bahwa upaya melawan alienasi yang menciptakan kelas sosial harus dimulai dari dalam jiwa setiap individu.
Kesadaran meniadakan kelas-kelas sosial berdasar harta yang bersifat materi keduniaan bukan semata pada konteks realitas melainkan juga moralitas. Masyarakat tanpa kelas dalam dimensi moral berarti meniadakan sifat dan sikap sombong, kikir, zalim menuju kesederhanaan, rendah hati, dermawan dan pengasih-penyayang kepada sesama manusia. Memiliki kekuasaan, kekayaan dan kepandaian, jangan membuat diri menjadi adigang-adigung-adiguna tetapi harus tetap rendah hati.
Aku sepakat dengan kritik Erich Fromm (pemikir sosialis Jerman) terhadap sosialisme komunis yang sering kali gagal memenuhi kebebasan manusia. Oleh karena itu proyek realisasi harus berfokus pada pengembangan individu, partisipasi akar rumput dan penghapusan alieansi. Erich Fromm menegaskan bahwa upaya mewujudkan sosialisme-komunis agar tidak mengabaikan aspek moral sehingga proyek realisasi tidak hanya sebatas merevolusi struktur ekonomi dari kepemilikan alat produksi (modal) oleh individu menuju kepemilikan kolektif.
Pemaknaan Zakat Sebagai Kesederhanaan
Dari analisis di awal itu aku melihat bahwa persoalan kelas tidak berhenti pada struktur ekonomi melainkan menjalar ke pembentukan watak moral individu. Sebagai seorang muslim, terdapat perintah zakat yang tertuang jelas dalam rukun Islam yang ketiga. Aku memaknainya bukan hanya sebatas hukum belaka tetapi lebih jauh ialah suatu nilai yang menyadarkan dan mewajibkan pengamalnya untuk senantiasa peduli kepada sesama umat manusia dan mengutamakan sikap rendah hati. Bahwa disetiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya.
Zakat pada jenis zakat mal (harta) bisa dipahami sebagai suatu sistem kontrol sosial terhadap perputaran ekonomi dalam masyarakat. Sirkulasi harta kekayaan dioptimalisasi agar tidak mandeg dan tertimbun dalam satu individu atau kelompok. Harta itu jika sudah terlalu besar nilainya dalam kepemilikan individu maka wajib sekian persen untuk diberikan kepada golongan mustahik (penerima zakat). Hal itu diperintahkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dimana yang kaya semakin jumawa dan yang miskin semakin sengsara, sehingga meminimalisir terbentuknya kelas sosial yang tajam.
Memahami perintah zakat bukan sebatas pada tataran real tetapi juga harus dipahami secara moral. Semangat berzakat untuk menyisihkan harta bukan sekadar menunaikan perintah agama melainkan upaya kita menumbuhkan sikap rendah hati, peduli dan pengasih-penyayang. Zakat adalah pengeluaran (pemberian) harta yang bersifat wajib, selainnya ada infaq dan shadaqah yang masih bisa kita lakukan karena nilainya tidak ditentukan dan bebas, semampu harta yang dimiliki. Zakat adalah latihan jiwa menuju pribadi yang penuh kesederhanaan.
Tanpa Kelas Sosial Dalam Dimensi Moral
Memperjuangkan gagasan sosialis-komunis atau kapitalis-liberal adalah proses panjang suatu peradaban. Pertentangan dua gagasan besar dunia itu adalah suatu keniscayaan dalam sejarah umat manusia. Berhasil atau tidak kedua gagasan itu dalam mendominasi dan mempengaruhi gaya hidup setiap individu, yang utama adalah kesadaran untuk meniadakan kelas-kelas sosial dalam jiwa. Meniadakan sikap sombong, kikir dan zalim menuju rendah hati, dermawan dan pengasih-penyayang. Memandang sesama manusia sebagai subjek yang setara tanpa membedakannya karena materi, uang dan harta.
Setiap individu yang sadar untuk meniadakan kelas-kelas sosial mulai dari jiwa dan pikirannya adalah wujud dari masyarakat tanpa kelas dalam dimensi moral. Kesadaran ini menjadi pondasi kokoh yang bisa membangun keseimbangan, keselarasan dan harmoni bagi kehidupan di masyarakat.
Pada akhirnya aku berpikir bahwa upaya menciptakan masyarakat tanpa kelas itu bukan hanya sebatas dalam dimensi real melainkan juga moral. Sebaik apapun kedua ideologi besar dunia itu berupaya mempengaruhi peradaban, tapi tidak dilandasi oleh individu yang jiwa dan pikirannya untuk sadar bersikap dan bersifat rendah hati, dermawan serta pengasih-penyayang maka yang tercipta hanyalah peradaban nihil, tak bernilai.
Jika tujuan meniadakan kelas sosial hanya dimaknai pada dimensi real maka ia tak pernah mati. Tapi hanya berpindah dari realitas masyarakat menuju jiwa setiap individu yang pada akhirnya membentuk pikiran kolektif

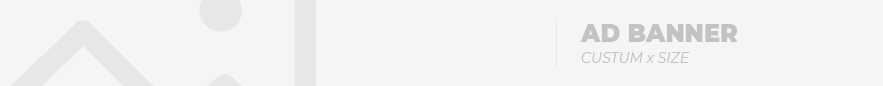

0 Komentar